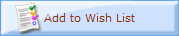|
|
Sinopsis Buku: Februari 2005
Siapa pun penonton televisi dan pembaca koran pasti ingat peristiwa nahas tersebut. Meutya Hafid,seorang reporter Metro TV dan Budiyanto, juru kamera yang mendampinginya, disandera oleh Mujahidin Irak. Mereka diculik tiba-tiba saat sedang berhenti di POM Bensin. Seluruh bangsa pun khawatir, berdoa demi keselamatan mereka, dan mengusahakan pembebasan secepatnya. 168 jam lamanya Meutya dan Budi berada dalam sandera. Di dalam sebuah gua kceil di tengah gurun Ramadi. Tidur beralaskan batuan dan dibuai oleh suara bom dan tembakan. Di sana mereka belajar tentang kepasrahan total kepada Yang Kuasa, karena telah begitu dekatnya dengan kata "mati". Di sana mereka diingatkan, bahwa jika Tuhan menghendaki, segalanya bisa terjadi. Dan, di sana pula mereka berdua disadarkan, betapa nyawa sangat berharga, dibandingkan berita paling ekslusif sekalipun. Resensi Buku:
     Malam, Kematian, Kemaluan Malam, Kematian, Kemaluan oleh: Rimbun Natamarga Lewat salah satu sajaknya, kita bisa tahu bahwa Chairil Anwar kagum pada orang-orang yang berani melewati malam, pergi menuju ketidakpastian yang ada di luar rumah pada malam hari, ketika jam malam ditabuhkan tentara-tentara pendudukan. Waktu itu, tentara Belanda mencoba untuk kembali menguasai Indonesia yang baru saja merdeka. �Aku suka pada mereka yang berani hidup,� tulis Chairil Anwar. �Aku suka pada mereka yang masuk menemu malam,� sebab kegelapan dapat menyembunyikan segala sesuatu, termasuk maut yang berdiam di moncong bedil orang-orang bersenjata. Kita bayangkan, ratusan orang berkeliaran tanpa suara dan hendak mencari suara-suara mencurigakan. Mereka saling mengintai dan mengancam. Bagi mereka yang pernah membaca Larasati Pramoedya Ananta Toer, pasti tahu lukisan kecamuk yang hadir pada waktu itu. Demikian pula dengan Di Tepian Kali Bekasi penulis yang sama, pasti ingat, betapa tokoh Farid memberontak dari ayahnya hanya untuk �menemui malam� seraya sadar bahwa kematian memperhatikannya mudah. Atau pada kisah dalam Tak Ada Hari Esok Mochtar Loebis, kita menyaksikan tentang �malam� itu, meski dalam penggalan-penggalan pendek. Tetapi mereka yang tahu tentang takdir pasti jauh lebih bijak. Bahkan dalam keadaan perang sekalipun, nasib ternyata sudah ditentukan. Manusia hanya berusaha, sebab, toh, setiap peluru yang meluncur lepas sudah memiliki nama-nama korbannya. Dan ketika mati, manusia pun pasti akan berfilosofi: masih untung mati, coba, kalau cacat� Kesadaran bahwa kematian itu dekat, rasanya, membuat kita juga harus bijak, betapa menyiksanya kesedihan yang menimpa orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita tinggalkan. Kita memang butuh perhitungan agar tak mati konyol. Bukan karena kita takut untuk mati, tapi justru karena kita sadar bahwa mati itu terlalu mudah dan hidup ternyata tak-gampang. Itulah pelajaran yang bisa saya ambil dari 168 Jam dalam Sandera tulisan Meutya Hafid. Dengan bahasa yang runtun�tentu saja dengan bantuan penulis-penulis pendampingnya�ia adalah reporter Metro TV yang menuliskan kembali pengalaman tegangnya ketika disandera olah salah satu faksi front Mujahidin di Irak. Cerita itu dimulai ketika ia dan salah seorang kamerawan Metro TV ditugaskan oleh pimpinan redaksi meliput pemilu di Irak. Irak pada saat itu memang baru usai dari pemerintahan Saddam Husein. Amerika dan beberapa negara sekutunya merekonstruksi Irak. Perlawanan rakyat Irak muncul. Bagi mereka, kekuatan asing yang membebaskan Irak dari Saddam itu berpotensi untuk menjadi penjajah baru di negeri mereka. Belum beranjak terbang menuju Jakarta, dua orang dari Metro TV itu kembali ditugaskan untuk meliput perayaan Asyura di Karbala. Tugas peliputan yang baru ini jelas mengundang bahaya. Dan mereka menyadari itu. biasanya, setiap perayaan di Karbala itu selalu mengundang keributan. Setiap tahun jatuh korban yang selalu bervariasi. Diduga, keributan yang terjadi itu akibat penyusupan oleh pihak Islam Sunni atau pihak-pihak luar Irak seperti Mossad Yahudi. Kebulatan tekad mengantarkan Meutya dan Budiyanto, kamerawan Metro TV itu, pada sebuah perjalanan yang tak pernah sampai ke Karbala. Di sebuah pom bensin di Ramadi, sebelum masuk Fallujah, mereka ditodong senapan oleh tiga orang tak dikenal. Mereka dibawa dan akhirnya disandera selama hampir 168 jam. Kesan yang dibangun Meutya dalam bukunya, saya rasa, berhasil. Kita dibawa pada kepanikan, ketegangan, dan ketakutan yang didapatinya. Kita akan mengunandika. Bagaimana jika itu terjadi pada kita? Bagaimana jika itu menimpa salah seorang anggota keluarga kita? Saya rasa, kita mampu melukiskannya, meski tidak akan terlalu mengena. Pada posisi yang sama, kita yang laki-laki akan merasakan satu ketakutan. Kematian�sebuah takut yang tunggal mewujud di benak kita. Tetapi, seperti Meutya, kita yang perempuan pasti akan mengalami dua ketakutan pada posisi disandera seperti itu. Pertama dan sudah jelas, adalah takut kematian. Yang kedua, takut diperkosa, dilecehkan secara seksual. Mati setelah diperkosa menghantui siapa pun perempuan itu. Apalagi kalau anda mengikuti semua pemberitaan tentang pembunuhan Marsinah tahun 90-an yang lalu. Menjadi perempuan, saya kira, betul-betul sulit. Mereka menghadapi dua ancaman ini, dua ketakutan ini dalam hidup. Mati dan diperkosa. Masih kita ingat beberapa bulan lalu, topik pelecehan seksual di angkutan-angkutan umum Jakarta diangkat di media-media massa. Mereka tidak dibunuh, tapi jelas mereka merasakan ketakutan dalam skala tertentu. Saya tak bermaksud membahas panjang lebar kasus-kasus itu. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa laporan-laporan yang muncul ke permukaan seperti itu hanya seperti puncak gunung es di lautan Atlantik. Kebanyakan, korban-korban pelecehan seksual, pemerkosaan, tidak akan berani mengangkat apa yang dialami mereka. Mereka memilih diam. Lebih baik menanggung derita perbuatan itu ketimbang menanggung rasa malu. Mereka adalah korban kebuasan laki-laki, juga korban sorotan lingkungan sekitar. Bahkan di Amerika Serikat sekalipun, salah seorang wanita korban pemerkosaan harus melewati tahun-tahun bisunya. Sebut saja namanya Rainey, usia 40 tahun. Ia malu dan takut dan itu bertahun-tahun, sampai suatu hari ia memberanikan diri mengungkap semua yang pernah dialaminya. Dan betapa publik terkejut. Bukan tentang kasus pemerkosaan itu sendiri, tapi perjuangan batin Rainey untuk kuat dan mengungkapkannya ke publik. Karena itu, menjadi seorang perempuan sudah pasti berat. Kita yang laki-laki ini terkadang malu juga menjadi laki-laki hanya gara-gara ulah sebagian kaum kita itu. Akan tetapi, atas alasan itu pula, kenapa para nabi dan orang-orang bijak betul-betul menghargai harkat perempuan, tidak untuk lalu menjadi perempuan, tapi untuk hidup bersama dan mendampingi seorang perempuan melewati kehidupan yang sebentar ini. Mereka menyadari, perempuan diciptakan dari tulang rusuk untuk hidup berbareng, tidak dilecehkan oleh mereka. Semua itu mereka tempuh, saya kira, agar ketakutan itu sendiri cuma satu, seperti yang kita laki-laki ini alami. Bukan dua.[]      oleh: kaochie kiswanto  Add your review for this book! Add your review for this book!
Buku Sejenis Lainnya:
 Advertisement |
 |
Hello.
 or or

|
 My BukaBuku | My BukaBuku |
 Cart | Cart |
 Help Help
|