|
|
Sinopsis Buku: Novel ini diawali dengan kisah latar belakang Jayantaka, Raja Kerajaan Ratnakanda yang menyaksikan konflik dan carut-marut keluarga kerajaan saat ayahnya masih menjadi raja. Berbagai ambisi terbuka akan kekuasaan dan jabatan, juga persaingan terselubung, politik istana yang saling tarik-menarik menyebabkan Ratnakanda perlahan berada di ambang kehilangan kedaulatan.
Kesadaran untuk membenahi kerajaan yang dilakukan Raja Ratnakanda justru mendapatkan perlawanan dari kerabat keluarga, hingga timbul kerusuhan yang tidak hanya mengorbankan nyawa tetapi juga hubungan persaudaraan. Jayantaka dinobatkan di masa perkabungan, dalam usia 16 tahun, yang secara keras dipersiapkan oleh ayahnya menjadi raja dengan tugas utama mengembalikan kedaulatan Ratnakanda. Jayantaka lalu menetapkan �dharma negara� dan �dharma agama�, yang didorong oleh kaulnya kepada Sang Hyang Kala, yakni perjanjian akan mempersembahkan 100 kepala raja, yang menyebabkan banyak negeri menjadi resah saat menyadari Jayantaka benar-benar memenuhi kaulnya juga tanpa kompromi menerapkan �dharma agama� yang diyakininya, yakni agama siwa. Karena tak cuma menaklukan wilayah juga menawarkan penerapan �dharma agama� yang diyakini, Jayantaka digelari Sang Porusadha, sang pelahap kepala raja. Di tengah kegelisahan itulah harapan ditumpahkan kepada Hastina, yang justru tengah gundah gulana ditinggal putra mahkotanya yang bernama Sutasoma, yang memilih bertapa daripada menikah dan menggantikan ayahnya menjadi raja. Berbagai bujukan baik dan para petapa bahkan Dewa Indra, tak juga membuat Sutasoma menganggap masalah Jayantaka itu masalah yang genting bagi kemanusiaan. Dia justru setiap saat menjelaskan mengenai jalan tengah, ajaran marga Buddha juga kelak meramalkan persatuan ajaran Siwa dan Buddha itu sebagai jalan tengah dari kemerosotan moral manusia. Sebaliknya, Dasabahu, ipar dari Sutasoma tidak bisa bersabar dengan pergerakan Jayantaka. Akhirnya pecah perang yang nyaris membumihanguskan seluruh kerajaan, andai saja Sutasoma tidak segera hadir, lalu menjelaskan mengenai kemanunggalan antara Siwa dan Buddha, bhinneka tunggal ika. Novel Sutasoma ini terinspirasi dari karya Empu Tantular, yang judul resminya adalah Porusadha, yang populer dengan nama Sutasoma; yang secara tradisi dibagi dalam dua versi. Yakni versi Bali dan Jawa. Dalam novel ini justru baru ditemukan proses ajaran Mahayana Tantra dan latar belakang Jayantaka; mengungkapkan pula jalan rahasia yoga tantra, kemudian tokoh-tokoh yang semula kabur dalam kisah lisannya dihidupkan dengan berbagai percakapan dan penjelasan mengenai ajaran Buddha Nusantara dan siwait, di latar belakangnya adalah kisah negara yang bangkit merebut kedaulatan dan bagaimana akibat apabila seorang raja menerapkan �dharma agama� dan �dharma negara� tanpa memperhitungkan kebhinekaan? Mungkinkah Sutasoma di era semacam Indonesia kini akan dihadirkan, untuk kembali menyuarakan �Bhinneka Tunggal Ika� di wilayah yang aneka warna ini? Di tengah hasrat menjadikan agama sebagai �dharma negara�? Novel sejarah yang ditulis seniman teater asal Bali, Cokorda Sawitri, ini seolah menyampaikan gagasan dan kritik halus untuk bangsa dan negerinya tercinta, Indonesia Raya, terutama kepada elite nasionalnya yang kini telah melupakan segalanya. Melupakan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang pemimpin bangsa, sebagaimana yang dilakukan Jayantaka kepada rakyat dan negerinya, Ratnakanda. Sebagai pemimpin, selayaknya bercermin kepada ketokohan Jayantaka. Dia berani menetapkan �dharma negara� dan �dharma agama�, yang diyakininya bisa mengubah cara pandang dan gaya hidup bangsawan dan keluarga istana yang korup, bermewah-mewahan, tanpa mau memerhatikan kesejahteraan rakyatnya. Novel Sutasoma ini layak menjadi bacaan bagi mereka yang peduli kepada negerinya. (Syafruddin Azhar, pengamat perbukuan dan senior editor di sebuah penerbitan di Jakarta) Resensi Buku:
Buku Sejenis Lainnya:
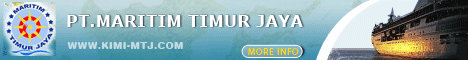 Advertisement |
 |
Hello.
 or or

|
 My BukaBuku | My BukaBuku |
 Cart | Cart |
 Help Help
|









