|
|
Sinopsis Buku: *Cetak ulang ganti cover*
Canting, carat tembaga untuk membatik, bagi buruh-buruh batik menjadi nyawa. Setiap saat terbaik dalam hidupnya, canting ditiup dengan napas dan perasaan. Tapi batik yang dibuat dengan canting kini terbanting, karena munculnya jenis printing---cetak. Kalau proses pembatikan lewat canting memerlukan waktu berbulan-bulan, jenis batik cetak ini cukup beberapa kejap saja. Canting, simbol budaya yang kalah, tersisih, dan melelahkan. Adalah Ni---sarjana farmasi, calon pengantin, putri Ngabean---yang mencoba menekuni, walau harus berhadapan dengan Pak Bei, bangsawan berhidung mancung yang perkasa; Bu Bei, bekas buruh batik yang menjadi ibunya; serta kakak-kakaknya yang sukses. Canting, yang menjadi cap batik Ngabean, tak bisa bertahan lagi. �Menyadari budaya yang sakit adalah tidak dengan menjerit, tidak dengan mengibarkan bendera.� Ni menjadi tidak Jawa, menjadi aeng---aneh, untuk bisa bertahan. Ni yang lahir ketika Ki Ageng Suryamentaram meninggal dunia, adalah generasi kedua, setelah ayahnya, yang berani tidak Jawa. Resensi Buku:
     Perjalanan Keluarga Bos Batik Perjalanan Keluarga Bos Batik oleh: Rimbun Natamarga Canting adalah sebuah wadah tembaga untuk membatik. Ketika membatik, canting ditiup agar cairan lilin di dalamnya tetap meleleh. Canting memantulkan suara nafas peniupnya. Sebagai alat membatik tradisional, canting memiliki fungsi penting sebelum muncul batik jenis printing (batik cetak). Dengan nama alat itulah, roman Arswendo Atmowiloto ini dijuduli. Canting berisi cerita tentang perjalanan hidup keluarga Ngabehi Sestrokusuma yang memiliki usaha pembatikan cap canting. Kepala keluarga adalah Raden Mas Daryono Sestrokusuma atau yang akrab dipanggil Pak Bei. Dengan Bu Bei, di nDalem Ngabean Sestrokusuman mereka berdua membesarkan enam orang anak; Wahyu Dewabrata, Lintang Dewanti, Bayu Dewasunu, Ismaya Dewakusuma, Wening Dewamurti, dan Subandini Dewaputri Sestrokusuma. Dalam usaha pembatikan itu, yang memegang peran penting adalah Bu Bei. Bersama seratus dua puluh buruh batik dengan aneka tugas masing-masing, Bu Bei menjalankan usaha. Perjalanan usahanya berlangsung bertahun-tahun, sampai Bu Bei bisa membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang perguruan tinggi. Dan sampai buruh-buruh batik itu dapat menghidupi keluarga masing-masing seraya mengabdikan diri untuk keluarga Sestrokusuma. Bertahun-tahun. Tidak seperti priyayi lainnya, Pak Bei adalah priyayi yang aneh. Aneh�karena ia berani mengambil sikap lain dari yang lain sampai dicap oleh priyayi-priyayi lainnya sebagai priyayi yang tidak nJawa. Namun, dalam keanehan itu terdapat sikap pasrah yang dijunjung tinggi olehnya. Hidup baginya adalah pasrah. Apa yang terjadi dihadapinya tanpa ragu. Ia menggelinding. Mengalir saja (hal. 359). Pasrah bukan berarti kalah, bukan pula mengalah (hal. 150), dan pasrah bukan mencari (hal. 233). Tapi pasrah adalah menyerah secara ikhlas, menerima. Pun pasrah bukan berarti memaksa diri untuk pasrah (hal. 238). Dalam sikap pasrah, tak ada penyalahan kepada lingkungan, orang lain, juga pada diri sendiri. Dan dalam pasrah, ternyata, bisa pula menjelma sikap yang aneh; tak lazim, tak lumrah. Bukan semata dibuat-buat, tapi aneh yang disadari; kalau memang harus aneh, tidak mengapa. Ini, bagi Pak Bei, untuk menguji peraturan yang dianggap telah sempurna (hal. 356-357), untuk mengembalikan kemungkinan tidak selaras. Jalan cerita Canting maju-mundur, melompat-lompat untuk merangkai kesatuan makna. Apabila bagian kesatu tampak seperti panggung di mana drama akan dan sedang dipertunjukkan, maka bagian ketiga menceritakan banyak �kejutan� yang terjadi dalam perjalanan kehidupan keluarga Sestrokusuman. �Kejutan��karena kesadaran pembaca dihantam bertubi-tubi lewat peristiwa-peristiwa lampau yang dialami oleh anak-anak Pak Bei. Ada konflik yang berdiam, bersembunyi, dan akhirnya meledak. Dan itu seringkali lewat penceritaan si bungsu; Subandini Dewaputri�pribadi aneh dalam keluarga setelah Pak Bei. Sering terasa bahwa penulis�melalui pribadi-pribadi yang �dipinjamnya��bercerita tentang segala peristiwa yang lewat, seperti orang yang meriwayatkan. Namun tiba-tiba, tanpa terasa, begitu saja alur cerita menjadi peristiwa yang terjadi saat itu. Yang seperti ini banyak terdapat pada bagian kesatu, ketika cerita masih berkisar tentang riwayat Pak Bei dan Bu Bei beserta anak-anaknya. Bagian yang paling singkat tapi menghentak-hentak adalah bagian kedua. Lewat kacamata seorang buruh batik, apa yang terjadi di kediaman Pak Bei dilukiskan. Karenanya, yang muncul adalah sebuah penafsiran dari seorang rakyat biasa terhadap peristiwa-peristiwa penting; semacam hasil pengamatan wong cilik. Lugu dan tentu saja lain, seolah ingin memberantaki apa yang selama ini kita anggap. Puncak dari �kejutan� yang muncul adalah ketika si bungsu mengutarakan keinginannya untuk meneruskan usaha pembatikan yang hampir bangkrut. Kejutan�sekali lagi, karena di sinilah konflik yang diam itu muncul dan menghantam kesadaran pembaca setelah sekian lama dianggap seperti tak ada lagi. Dan inilah yang menghantar�dan tepatnya merangkai�pembaca pada apa yang ditemakan dalam cerita: pasrah, sikap pasrah dalam pribadi Pak Bei. Sayangnya, konflik yang dapat membuat pembaca asyik menerka lagi meraba-raba itu akhirnya diselesaikan penulis dengan mematikan Bu Bei. Seakan-akan hanya itu jalan keluar. Bagi pembaca-aktif (a reader) yang mengeksplorasi permasalahan di dalamnya, memang satu-satunya jalan keluar adalah dengan mematikan Bu Bei. Padanyalah kunci permasalahan itu, sebagaimana yang dijelaskan panjang-lebar oleh Pak Bei pada si bungsu ketika menanggapi keinginannya untuk meneruskan usaha pembatikan (lihat hal. 233-235 & 238). Tentang �ending� cerita, apa yang telah disajikan dan dirangkai dalam Canting, terkesan kuat diakhiri dengan tergesa-gesa. Entah apa maksud penulis, yang jelas, mulai halaman 362 (sampai halaman 377) cerita mengalir cepat dan cepat seolah-olah ingin buru-buru cari jalan keluar. Bukan mengada-ada, tapi begitulah yang terkesan. Emosi yang sudah teraduk-aduk dengan baik pada halaman-halaman sebelumnya dipaksa reda begitu saja. Padahal, pada halaman-halaman sebelumnya itu, lelucon yang disajikan penulis lewat ucapan-ucapan para pelaku terasa mengena. Efek lucu dapat dipahami bila terasa mengena, karena tampil dalam komentar-komentar menyimpang pada kondisi-kondisi tertentu yang kita tahu bagaimana seharusnya. Seperti percakapan antara si bungsu dengan salah seorang buruh batik tentang kapan rencana pernikahan (hal. 204). Atau percakapan si bungsu dengan seorang tukang becak tentang tawar-menawar ongkos � la Solo ketika pulang dalam rangka merayakan ulang tahun Pak Bei (hal. 154). Atau juga�ini yang ekstrem (!)�komentar-komentar Pak Bei tentang kematian Bu Bei, yang bertebar pada halaman 254, 255, dan 257. Meski demikian, apa yang diungkapkan sampai di sini adalah sebuah hasil pembacaan atas teks. Bagaimana pun hasilnya, semua berangkat dari keinginan untuk semata-mata membaca lalu menuliskan kembali apa yang didapat dari karya Arswendo ini. Sebab di dalamnya ada sesuatu yang dapat ditafsiri. Ada sesuatu yang mesti dilukiskan kembali oleh pembaca, tentu saja: walaupun Canting sudah lama tak beredar di pasaran. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, Canting tampaknya bukan sembarang karya. Tidak kurang dari Andries de Teeuw, pengamat sastra Indonesia dari Leiden itu, pernah memberikan tanggapannya tentang Canting ini dalam kumpulan tulisannya; Keberlisanan dan Keberaksaraan (Pustaka Jaya). Adapun Umar Kayam yang pernah memerankan Pak Bei dalam sinetron Canting, membeberkan sedikit suka-dukanya selama shooting di Solo dalam kumpulan kolomnya, Satrio Piningit ing Kampung Pingit: Mangan Ora Mangan Kumpul 4 (Grafiti Pers). Bagi yang pernah membaca Para Priyayi (Grafiti Pers) dan kebetulan puas atau justru merasakan kerinduan yang sangat untuk menikmati lagi karya-karya yang setema dengannya, Canting ini adalah salah satu alternatif yang paling baik. Dan agaknya tidak berlebihan pula bila dikatakan bahwa �sekuel� Para Priyayi pun, yakni Jalan Menikung (Grafiti Pers), tak dapat menyamainya.  Add your review for this book! Add your review for this book!
Buku Sejenis Lainnya:
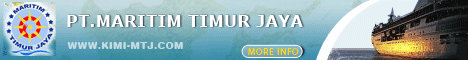 Advertisement |
 |
Hello.
 or or

|
 My BukaBuku | My BukaBuku |
 Cart | Cart |
 Help Help
|














